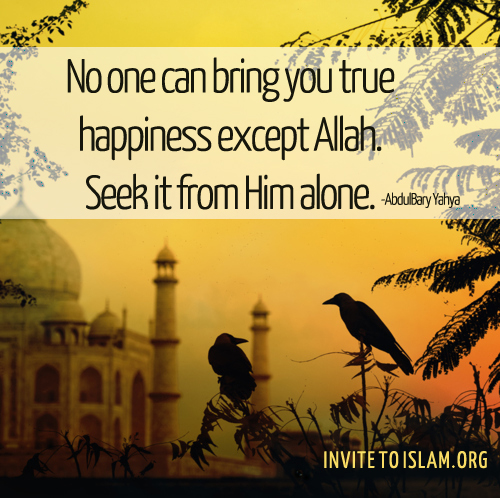Makna bahagia dapat dipahami secara harfiah dari kata al-insan (manusia) itu sendiri yang dalam al-Qur’an disebut sebanyak 65 kali. Menurut Quraish Shihab, kata al-insan berasal dari akar kata yang berarti “jinak”, “harmonis”, “gerak/dinamis“, “lupa”, dan “merasa bahagia/senang”. Ketiga arti ini menggambarkan sebagian dari sifat atau ciri khas manusia: ia bergerak dan dinamis, memiliki sifat lupa dan dapat melupakan kesalahan-kesalahan orang lain, atau merasa bahagia dan senang bila bertemu dengan jenisnya, bahkan idealnya selalu berusaha memberi kesenangan dan kebahagiaan kepada diri dan makhluk- makhluk lainnya. Hal ini juga berarti bahwa manusia berpotensi untuk selalu merasa senang, bahagia, dan membahagiakan orang lain. Itulah misi hidup manusia di muka bumi ini.
Makna dan Hakikat Kebahagiaan dalam al-Qur’an
1. Kehidupan yang baik
Makna ini dapat dilihat dalam dua ayat berikut ini:
“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. an-Nahl: 97).
“Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di daratan dan lautan, dan Kami telah memberikan rezeki yang baik kepada mereka, dan Kami telah lebihkan mereka dari makhluk- makhluk lain yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (QS. Al-Isra: 70).
“Orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik” (QS. ar-Ra’du, 13: 29).
Dalam Tafsir al-Mishbah Quraish Shihab menjelaskan bahwa ungkapan “kehidupan yang baik” di atas mengisyaratkan bahwa seseorang dapat memperoleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang berbeda dengan kebanyakan orang. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kehidupan yang baik itu bukan berarti kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah.
Dengan demikian, orang yang memiliki kehidupan yang baik tidak merasakan takut yang mencekam atau kesedihan yang melampaui batas, karena dia selalu menyadari bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik, dan di balik segala sesuatu ada ganjaran yang menanti. Seorang yang durhaka, meskipun kaya, dia tidak akan pernah merasa puas, selalu ingin menambah kekayaannya, sehingga selalu merasa miskin dan diliputi kegelisahan, rasa takut tentang masa depan dan lingkungannya. Dia tidak menikmati kehidupan yang baik.
Kehidupan yang baik juga dapat dipahami sebagai kehidupan di surga kelak, alam barzakh, atau kehidupan yang diwarnai oleh qona’ah, yaitu rasa puas atas sesuatu (rizki) yang halal.
Berikut adalah pendapat ahli terkait dengan kehidupan yang baik :
-
Dalam Tafsir al-Azhar, HAMKA menyatakan bahwa kehidupan yang baik adalah anugerah Allah yang dijanjikan kepada orang yang beriman dan beramal shalih di dunia ini.
-
Ibnu Katsir mengartikan kehidupan yang baik dengan ketenteraman jiwa, meskipun banyak menghadapi gangguan.
-
Bagi Ibnu Abbas, kehidupan yang baik adalah mendapatkan rizki yang halal lagi baik dalam hidup di dunia ini.
-
Menurut Ali bin Abi Thalib, kehidupan yang baik adalah rasa tenang dan sabar menimpa berapapun dan apapun yang diberikan Allah, dan tidak merasa gelisah.
-
Sementara, Ali bin Abi Thalhah dan Ibnu Abbas memaknai kehidupan yang baik dengan as-sa’adah atau rasa bahagia. Satu riwayat dari ad-Dahhaak menyatakan bahwa kehidupan yang baik ialah rizki yang halal, kelezatan dan kepuasan beribadah kepada Allah dalam hidup, dan lapang dada.
-
Menurut Ja’far as-Shadiq, kehidupan yang baik adalah tumbuhnya ma’rifah atau pengenalan terhadap Allah di dalam Jiwa.
-
Menurut al- Mahayami, kehidupan yang baik adalah ketika seorang mukmin merasa berbahagia dengan amalnya di dunia ini, lebih daripada kesenangan orang yang berharta dan berpangkat dengan harta dan pangkatnya, dan kebahagiaan perasaannya itu tidak ditumbangkan oleh kesulitan hidupnya. Hal itu terjadi karena yang bersangkutan merasa ridho menerima pembagian yang diberikan Allah kepadanya, sehingga harta benda tidak terlalu dipentingkannya. Sebaliknya, orang kafir, meskipun banyak harta, dia tidak pernah merasa bahagia, malah tambah rakus dan takut bila hartanya akan habis. Sementara itu, orang yang diberikan kehidupan yang baik di dunia ini akan juga diberi ganjaran yang lebih baik di akhirat.
-
Menurut al-Qasimi, kehidupan yang baik adalah rasa sejuk (tenteram) dalam dada karena puas dan yakin, merasakan manisnya iman, ingin menemui apa yang telah dijanjikan Allah dan ridha menerima ketentuan (qadha) dari Tuhan. Selanjutnya, jiwanya dapat melepaskan diri dari apa yang telah memperbudaknya selama ini, merasa tenteram dengan satu Tuhan yang disembah, serta mengambil cahaya (nur) dari rahasia wujud yang berdiri padanya, dan lain-lain kelebihan yang telah ditentukan pada tempatnya masing-masing. Itulah kehidupan yang baik di dunia, adapun kehidupan keakhirat akan lebih baik dan sempurna ganjarannya.
Kata HAMKA, semua penafsiran di atas tidak berlawanan, tetapi saling melengkapi, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits:
“Sungguh bahagia orang yang telah ditunjukkan kepada Islam (menjdai muslim), mendapat rezeki sekedar cukup, dan menerima dengan senang apa yang diberikan Allah kepadanya.” (HR. Imam Ahmad dari Ibnu Umar).
Intinya, kata Hamka, sesunggnya segala amal saleh yang dikerjakan oleh manusia yang bersumber dari rasa iman tidaklah sepadan dengan pahala dan ganjaran yang akan kita terima di akhirat kelak. Sesungguhnya, amal yang dikerjakan manusia sangatlah sedikit, tetapi ganjaran yang ia terima berlipat ganda. Umur manusia terbatas, sementara balasan terhadap amal manusia tidak pernah habis dan selalu kekal.
Itulah makna kebahagiaan dalam arti kehidupan yang baik yang merupakan naluri spiritual yang khas manusia, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Isra: 70. Artinya, pada dasarnya bahagia adalah fitrah bagi manusia. Bahagia sudah seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, karena menurut fitrahnya, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kesempurnaan. Manusia adalah makhluk yang paling baik dan sempurna dibanding dengan makhluk lainnya.
Kabir Helminski, seorang sufi penerus tradisi Jalaluddin Rumi, menulis tentang manusia sempurna dalam bukunya, The Knowing Heart: A Sufi Path of Transformation. Menurut tokoh ini, sifat manusia sempurna adalah refleksi dari sifat-sifat Tuhan yang sebagian tercermin dalam 99 nama Allah (al-Asma’ul Husna). Kesempurnaan manusia adalah takdir bawaan manusia, yang memerlukan hubungan yang harmonis antara kesadaran diri dan rahmat Ilahi. Itulah capaian kebahagiaan yang sesungguhnya.
2. Kebaikan
Kebahagiaan dalam arti kebaikan atau yang baik dapat dipahami dari QS. at-Taubah: 50; ar-Ra’du: 6,22; an-Nahl: 30,41,122; an-Naml: 46,89; al-
Qashash: 54, 84; al-Ahzab: 21; az-Zumar: 10; Fushshilat: 34; as-Syuura: 23; dan al-Mumtahanah: 4,6.
“Dan kami beri dia di dunia ini kebaikan, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang- orang yang shaleh” (QS an-Nahl: 122).
HAMKA menjelaskan tentang kandungan ayat ini dengan melihat anugerah (kebahagiaan) yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim AS. Maksudnya adalah bahwa kebaikan dunia yang telah nyata diterima oleh beliau adalah ketika beliau nyaris tidak mengharapkan lagi akan mendapatkan keturunan (putera), karena usianya yang telah menua, maka kemudian beliau memiliki putera (Ismail) pada usia 86 tahun. Kemudian pada usia 100 tahun beliau memiliki anak kedua (Ishaq) dari isteri beliau yang diduga mandul, yaitu Sarah. Kedua putera inilah yang kemudian menurunkan bangsa-bangsa besar. Selain itu, HAMKA melihat dari rizki yang diperoleh Ibrahim yang berlipat ganda di hari tuanya. Sudah menjadi hal yang lumrah (umum) bahwa keturunan dan harta benda adalah lambang kebaikan dunia dan kemegahannya. Sungguh sebuah keniscayaan, jika orang yang telah berjuang demi Allah, sebagaimana Ibrahim yang telah mendapat gelar “Khalilullah”, akan mendapatkan tempat yang layak pula di akhirat, bersama orang-orang shalih lain, yaitu para Nabi, Rasul, dan para pengikutnya yang setia.
Kata hasanah, yang berarti kebaikan dapat ditemukan pula dalam QS. ar- Ra’du: 6 sebagai berikut:
“Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan (datangnya) siksa sebelum (mereka meminta) kebaikan, padahal telah terjadi bermacam- macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan (yang luas) bagi manusia sealipun mereka dzalim, dan sesunggunya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksa-Nya.
Al-Maraghi menjelaskan makna hasanah dalam ayat di atas sebagai balasan bagi orang yang beriman, yaitu berupa kemenangan dan keberuntungan di dunia serta pahala di akhirat. Dalam konteks ayat di atas, kata hasanah merupakan lawan dari kata sayyiah yang berarti azab yang diancamkan kepada orang-orang kafir. Janji ini sesungguhnya telah disampaikan oleh Nabi Saw. kepada kaum kafir agar mereka mau beriman, tetapi yang terjadi adalah justru mereka minta (menantang) kepada Nabi untuk disegerakan azab buat mereka.
Sementara, dalam menjelaskan makna hasanah (kebaikan) dalam QS. at- Taubah ayat 50, al-Maraghi mengartikannya sebagai sesuatu yang apabila tercapai akan menyenangkan jiwa, seperti harta rampasan perang, kemenangan, dan sebagainya. Intinya, kata al-Maraghi, kebaikan adalah segala hal yang membuat manusia gembira, seperti kemenangan dan rampasan perang yang didapatkan oleh umat Islam waktu Perang Badar.
Hasanah dalam ayat ini dapat dipahami secara berpasangan dengan mushibah yang dapat diartikan sebagai kesusahan, kekalahan, atau tercerai-berainya tentara umat Islam waktu Perang Uhud.
Berangkat dari berbagai penafsiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna hasanah adalah segala kebaikan yang menimbulkan rasa bahagia, yang didapatkan manusia di dunia; berupa kemenangan, rizki, kejayaan, kesuksesan, anak, harta benda, dan sebagainya, dan di akhirat sebagai balasan yang lebih kekal yang sifatnya lebih ruhani. Kebaikan dunia dan akhirat inilah yang akan didapatkan bagi orang-orang yang beriman dan berjuang di jalan Allah.
3. Bahagia atau beruntung
Makna bahagia atau beruntung dapat disimpulkan dari redaksi kalimat yang terdapat dalam dua ayat berikut ini:
“Di kala datang hari itu, tidak ada seorangpun yang berbicara melainkan dengan seijin-Nya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia” (QS. Huud: 105)
“Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan- Mu menghendaki (yang lain), sebagai karunia yang tiada putus-putusnya” (QS. Huud: 108)
Istilah kebahagiaan dalam dua ayat di atas dapat dipahami dalam konteks dualitas, yaitu merupakan lawan dari kata celaka (sengsara). Kesadaran manusia pada dasarnya selalu bersifat dualistis. Artinya, kehidupannya di setiap tempat dan waktu merupakan polarisasi yang tajam antara sakit dan lezat, bahagia dan derita. Ia akan selalu berhadapan dengan kesusahan atau kesenangan, bahagia atau sengsara. Manusia akan selalu berhadapan dengan dua realitas ini, yaitu kesenangan atau kesusahan, termasuk ekspresinya, yaitu tertawa atau menangis.
Tangisan adalah tanda kesedihan atau sesuatu yang menyakitkan, sedangkan tertawa adalah bukti kebahagiaan, kegembiraan, atau kesenangan. Orang yang bahagia biasanya menampakkan wajah yang penuh senyuman atau berseri-seri. Sebaliknya, orang yang sedih biasanya menunjukkan wajah yang muram atau penuh tangisan. Orang yang sengsara adalah orang yang sesat, tidak tahu jalan hidup yang harus ditempuh, tidak sadar apakah ia berbuat benar atau salah, atau tidak dapat membedakan mana yang hak dan yang batil.
Orang yang bahagia adalah kebalikan dari itu. Jiwanya tenang, hati tenteram, tenang menghadapi persoalan, hatinya disinari cahaya iman kepada Allah, di dalam jiwanya tertanam akidah yang kuat, dan sadar bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah Swt.
Orang bahagia adalah orang yang merasa aman, tenang, dan punya kekuatan untuk menjalani kehidupan, sebagaimana firman Allah di bawah ini: 54
“Lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan ia tidak akan celaka.” (QS. Thaha: 123)
Sementara itu, makna kebahagiaan dalam arti lainnya, yaitu kata aflaha terambil dari kata falah yang diartikan sebagai ”memperoleh yang dikehendaki”. Kata ini sering diterjemahkan dengan “beruntung”, “berbahagia”, memperoleh kemenangan, dan sejenisnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, kata aflaha ditemukan dalam al-Qur’an sebanyak empat kali, salah satunya adalah QS.Thaha: 64, yang merupakan ucapan Fir’aun ketika akan terjadi pertandingan sihir antara Nabi Musa dan ahli-ahli sihirnya:
“Pasti memperoleh keberuntungan (kebahagiaan) siapa yg hari ini lebih tinggi sihirnya” (QS. Thaha: 64).
Menurut Quraish Shihab, kata aflaha merupakan penegasan Allah Swt. yang ditemukan pada surat al-a’la ayat 14, as-Syams ayat 9, dan al- mu’minun ayat 1. Dalam al-Mu’minun ayat 1-9, dikemukakan sifat-sifat orang-orang mukmin yang akan meraih al-falah (kemenangan). Sifat-sifat tersebut mencerminkan pula usaha-usaha mereka (orang-orang yang beriman) yang pada akhirnya dapat dinilai sebagai upaya penyucian diri (tazakka), sebagaimana ada di QS. Al-A’la.
Upaya-upaya itu meliputi khusyu dalam shalat, menunaikan zakat, menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, menjaga kemaluan kecuali pada pasangan yang sah, memelihara amanat dan janji, dan memelihara waktu shalat.
Dalam QS. Al-a’raf 157 ditegaskan pula bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi Saw., memuliakan, dan membela beliau, termasuk orang-orang yang beruntung. Selain itu ditegaskan pula dalam QS. Al-Qashahsh 67:
“Adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amal saleh, maka semoga dia termasuk yang beruntung”.
Jadi, mengamalkan sifat (pekerjaan) di atas akan mengantarkan seseorang memperoleh keberuntungan sekaligus menjadikan jiwanya suci dan bersih.
Di sisi lain, ditemukan pula lima sifat atau perbuatan yang secara tegas dinyatakan Qur’an sebagai faktor yang tidak akan membawa keberuntungan (kebahagiaan), yaitu: penganiayaan (QS. 6: 21), kriminalitas (QS. 10: 17), sihir (QS. 10: 77), kekufuran (QS. 23: 117), dan kebohongan dengan mengatasnamakan Allah (QS. 10: 69).
Penegasan al-Qur’an yang berbicara tentang orang yang memperoleh keberuntungan cenderung dituntut untuk melakukan sifat (pekerjaan) yang tidak ringan. Maka, sangat tidak tepat jika tazakka dalam QS. Al-A’la 14-15 ditasirkan dengan sekedar zakat fitrah dan Shalat ‘Id sebagaimana dipahami oleh sebagian mufassir.
Dengan melihat berbagai penafsiran di atas, maka makna kebahagiaan dalam arti falah, sa’adah, dan fauz lebih bersifat umum, meliputi kesenangan, kegembiraan, dan keberuntungan yang didapatkan oleh orang- orang yang beriman, bertaqwa, beramal saleh, serta mengikuti petunjuk Allah dengan cara mengikuti para rasul-Nya. Kebahagiaan ini berdimensi fisik, psikis, dan spiritual, baik di dunia maupun di akhirat.
4. Ketenangan dan ketenteraman
Kebahagiaan dalam arti ketenteraman dan ketenangan dapat digali dari dua lafadz di atas sebagaimana tersebar dalam ayat-ayat al-Qur’an.
Dua istilah di atas, yaitu ketenangan (sakinah) dan ketenteraman (thuma’ninah), sering dipertukarkan penggunaannya. Akan tetapi, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dua istilah ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu:
-
Sakinah merupakan keadaan secara tiba-tiba yang terkadang disertai dengan hilangnya rasa takut, sedangkan thuma’ninah merupakan pengaruh yang timbul dari adanya sakinah. Ringkasnya, thuma’ninah merupakan puncak dari sakinah.
Keberuntungan yang diperoleh karena sakinah seperti seseorang yang berhadapan musuh. Artinya, ketika musuhnya sudah lari, maka hati yang bersangkutan menjadi tenang. Sedangkan thuma’ninah seperti orang yang masuk ke dalam benteng yang pintunya terbuka, sehingga dia merasa aman dari musuh.
-
Thuma’ninah sifatnya lebih umum, karena ditunjang oleh ilmu, pemberitaannya, keyakinan, dan dan keberuntungan. Sebagai contoh misalnya, hati menjadi thuma’ninah karena bacaan al-Qur’an. Hal ini terjadi karena ada rasa iman kepada al-Qur’an, mengetahuinya, dan mendapat petunjuknya. Sementara, sakinah merupaka keteguhan hati yang dapat mengusir rasa takut dan hilangnya kecemasan, seperti keadaan pasukan Allah yang dapat membunuh musuh.
Secara sufistik, sakinah (ketenangan) termasuk tempat persinggahan pemberian dan bukan pencarian atau usaha. Artinya, sakinah adalah ketenangan yang diturunkan Allah ke dalam hati hamba-Nya ketika mengalami keguncangan dan kegelisahan karena ketakutan yang mencekam. Setelah itu, dia tidak lagi merasakannya, karena ketakutan itu sudah disingkirkan, sehingga menambah keyakinan, keimanan, dan keteguhan hatinya.
Menurut Sayyid Quthb, ketika menafsirkan QS al-Fath: 5, sakinah merupakan istilah yang mengungkapkan, menggambarkan, dan menaungi. Apabila sakinah diturunkan Allah ke dalam hati manusia, terjadilah ketenteraman, ketenangan, keyakinan, kepercayaan, kekokohan, keteguhan, kepasrahan, dan keridhoan. Dalam pembukaan surat ini Allah menurunkan berita kebahagiaan untuk Rasulullah, yaitu berupa kemenangan yang nyata, ampunan yang menyeluruh kenkmatan yang sempurna, hidayah yang kokoh, dan pertolongan yang kuat. Akan tetapi, dalam ayat kelima ini Allah selanjutnya juga menjelaskan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kaum mukminin berupa kemenangan, sentuhan ketenteraman dalam hati mereka, dan nikmat lainnya yang tersimpan untuk mereka di akhirat.
Menurut Ibnu Taimiyyah, sakinah dapat dibedakan dalam tiga derajat, yaitu :
-
Derajat pertama, yaitu sakinah kekhusyu’an saat melaksanakan pengabdian, berupa memenuhi hak, mengagungkan, dan menghadirkan hati di hadapan Allah. 62 Sakinah model ini berarti ketenangan, kewibawaan, dan kekhusyu’an yang diperoleh pelakunya karena berbuat kebajikan. Allah berfirman:
“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka)?” (QS. al-Hadid: 16)
Karena iman mengharuskan munculnya kekhusyu’an atau mengajak kepada kekhusyu’an, maka Allah menyeru orang-orang yang beriman dari kedudukan iman kepada kebajikan. Dengan kata lain, Allah berfirman: “Belumkah tiba saatnya bagi mereka untuk mencapai kebajikan dengan iman?” Untuk mewujudkannya hal ini orang yang beriman memerlukan kekhusu’an saat mereka mengingat apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Yang dimaksud memenuhi hak dalam derajat ini adalah memenuhi hak pengabdian kepada Allah Swt., yaitu saat seseorang memiliki rasa pengagungan dan hadirnya hati saat menyaksikan Allah yang disembah, seakan-akan ia dapat melihat-Nya.
-
Derajat yang kedua, yaitu sakinah saat bermuamalah, dengan menghisab diri, lemah lembut terhadap makhluk, dan memperhatikan hak Allah. Derajat inilah yang biasa dimiliki oleh para sufi dan yang menjadi ciri mereka dalam bermuamalah dengan Allah dan makhluk, yang diperoleh dengan tiga hal, yaitu menghisab diri, lemah lembut terhadap makhluk, dan memperhatikan hak Allah.
Menghisab diri adalah senantiasa menghitung diri dan bertanya terhadap diri sendiri tentang kekurangan setiap amal yang dilakukannya di hadapan Allah, sebagai bahan perbaikan. Lemah lembut terhadap makhluk adalah tidak memperlakukan mereka, khususnya manusia, dengan kaku dan keras, karena hal ini akan membuat mereka lari menghindar, merusak hati dan hubungan dengan Allah, dan membuang waktu. Sebaliknya, seorang mukmin yang memiliki sakinah akan dapat berinteraksi dengan manusia secara lemah lembut.
-
Derajat sakinah yang ketiga adalah sakinah yang menguatkan keridhaan terhadap bagian dirinya, mencegah dari omong kosong dan menempatkan orang yang memilikinya pada batasan ubudiyah. Sakinah ini tidak turun kecuali ke dalam hati para nabi, wali, dan orang yang terpilih dari hamba-hamba Allah. Orang yang memiliki sakinah jenis ini merasa ridha kepada bagian dirinya dan tidak menoleh ke bagian orang lain. Orang yang memiliki sakinah tidak akan berkata bohong, karena dusta hanya muncul dari hati yang tidak memiliki sakinah. Ini adalah anugerah yang paling agung yang dikaruniakan Allah hanya kepada para Rasul dan orang-orang mukmin sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.
Tentang thuma’ninah, dengan merujuk pada QS. al-Fajr: 27-30, Ibnu Qayyim mengartikannya sebagai ketenteraman hati terhadap sesuatu, tidak cemas dan gelisah. Di dalam atsar disebutkan bahwa “Kejujuran merupakan ketenteraman dan kebohongan merupakan kebimbangan”.
Allah menjadikan thuma’ninah di dalam hati orang-orang beriman dan di dalam jiwa mereka, kemudian memberikan kabar gembira, bahwa yang masuk sorga adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang tenteram (thuma’ninah). Ayat yang berbunyi:
“Hai jiwa yang tenteram, kembalilah kepada Tuhanmu”, merupakan dalil bahwa jiwa itu tidak kembali kepada Allah kecuali jika dalam keadaan thuma’ninah. Orang yang beriman dianjurkan untuk membaca do’a ulama salaf, sebagai berikut: “Ya Allah anugerahkanlah kepadaku jiwa yang thuma’ninah kepada-Mu”.
Sebagaimana sakinah, thuma’ninah oleh Ibnu Qayyim dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:
-
Thuma’ninah hati karena menyebut asma Allah Swt. Ini merupakan thuma’ninah-nya orang yang takut yang beralih ke harapan, dari kegelisahan ke hokum, dan dari cobaan ke pahala. Sifat thuma’ninah jenis ini bisa dipahami dari rasa tenang yang muncul karena menyebut nama Allah dan membaca kitab-Nya dan rasa tenteram yang dimiliki oleh hati seorang hamba yang merasa takut akan siksa-Nya, kemudian beralih ke rasa harap akan kasih sayang-Nya. Demikian halnya dengan rasa tenteram seseorang karena mengikuti hukum-hukum agama yaitu dengan mengikuti jalan yang lurus serta huku takdir, di mana Allah telah berkehendak akan seperti apa dan bagaimana nasib seorang hamba dengan takdir dan kekuasaan-Nya, atau rasa tenteram seorang hamba yang awalnya gelisah karena mendapat berbagai cobaan dari Allah, tetapi kemudian menjadi tenang karena yakin akan pahala atau pengganti yang dijanjikan oleh Allah Swt.
-
Thuma’ninah ruh saat mencapai tujuan pengungkapan hakikat, saat merindukan janji, dan saat berpisah untuk berkumpul kembali. Ruh menjadi thuma’ninah jika melihat tujuannya dan tidak ingin menengok ke belakang. Ruh akan merindukan apa yang dijanjikan kepadanya. Ia menjadi tenang dan tenteram karena yakin akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepadanya. Ruh juga menjadi thuma’ninah jika ia berpisah denga hal-hal yang menjadi kebiasaannya, seperti orang yang lapar lalu mendapatkan makanan, yang membuatnya menjadi tenteram.
-
Thuma’ninah karena menyaksikan kasih sayang Allah, kebersamaan menuju kekekalan, dan kedudukan menuju cahaya azali. Derajat ini terkait dengan kefanaan dan kekekalan yang akan dialami oleh Ruh. Orang yang sampai kepada kesaksian kebersamaan dengan Allah akan merasa tenteram karena kasih sayang Allah. Ia juga tenteram karena yakin akan segala ketetapan Allah yang bersifat azali.
Berangkat dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan dalam arti sakinah (tenang) dan thuma’ninah (tenteram) adalah segala balasan, anugerah, dan nikmat dari Allah yang lebih bernuansa psikologis (emosi/perasaan), ruhaniyah (spiritual), dan ukhrowi, dari pada sekedar kebahagiaan yang bersifat material, jasadiyah, dan duniawi. Setiap muslim akan berusaha menggapai kebahagian jenis ini, karena merupakan puncak kebahagiaan atau kebahagiaan yang sesungguhnya.
5. Kelapangan dan kegembiraan
Makna kebahagiaan dalam kata lapang atau melapangkan dapat digali dari QS. al-Insyirah: 1. Menurut Quraish Shihab, kata ini berarti memperluas atau melapangkan, baik secara material maupun immaterial. Apabila kata ini dikaitkan dengan sesuatu yang material, maka ia berarti ‘memotong’ atau ‘membedah’, sedangkan jika dikaitkan dengan sesuatu yang non material, maka ia berarti ‘membuka’, ‘memberi pemahaman’, atau ‘menganugerahkan ketenangan’.
Dengan memperhatikan konteks QS. al-Insyirah dan ayat-ayat lainnya, misanya QS. az-Zumar: 22, al-An’am: 125, al-Hajj: 46, dan sebagainya, maka kata lapang lebih tepat dipahami kaitannya dengan sesuatu yang immaterial. Makna kelapangan dalam dalam ayat-ayat di atas lebih tepat dipahami sebagai kelapangan dada yang dapat menghasilkan kemampuan menerima dan menemukan kebenaran, hikmah dan kebijaksanaan, dan kesanggupan menampung bahkan memaafkan kesalahan orang lain.
Makna kebahagiaan dalam bentuk kata kegembiraan dapat ditemukan dalam beberapa tempat, yaitu: QS. Ali Imran: 120, 170, 188; al-An’am: 44; at-Taubah: 50, 81; Yunus: 22, 58; Huud: 10; ar-Ra’du: 26,36; al-Mu’minun: 53; an-Naml: 36; al-Qashash: 76; ar-Ruum; 4, 32, 36; al-Ghafir: 75,83; asy-Syuuraa: 48; dan al- Hadiid: 23.
Kata ini, terutama dalam konteks QS Ghafir: 75 , menurut ar- Raghib al-Ashfahani, digunakan dalam arti keceriaan dan kegembiraan hati akibat adanya kelezatan duniawi yang pada umumnya berupa kelezatan yang bersifat jasmaniah.
Pada dasarnya, menurut Quraish Shihab, kegembiraan dan keceriaan tidaklah dilarang agama, sehingga dalam ayat ini ada kata “tanpa hak”, karena bisa saja ada kegembiraan yang dibenarkan agama.
Berangkat dari penafsiran di atas, dengan melihat isyarat dari ayat-ayat yang lain yang menggunakan kata fariha, maka dapat disimpulkan bahwa makna kebahagiaan dalam kata ini bukanlah kebahagiaan yang obyektif dan pasti, tetapi merupakan kebahagiaan bersifat yang relatif, subyektif, dan dan belum tentu dibenarkan oleh agama. Artinya, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. at-Taubah: 81, bisa saja ada orang (di jaman Nabi) yang merasa gembira tidak ikut berjuang (berjihad) di bawah pimpinan Rasulullah atau melalaikan kewajiban agama. Gembira model ini oleh HAMKA di katakan sebagai kegembiraan orang munafik yang tidak sesuai dengan agama.
Dalam konteks sekarang, apabila banyak dijumpai orang yang tidak beriman, tidak menjalankan ajara agama, atau melanggar aturan-aturan, atau bermaksiat kepada Allah, tetapi mereka merasa bahagia, gembira, senang, dan tertawa. Mereka tidak menyadari bahwa perilakunya akan membawa kesengsaraan di kemuadian hari. Maka, kebahagiaan yang semacam ini bukanlah kebahagiaan yang diperintahkan (dimaksud) oleh al-Qur’an untuk digapai oleh manusia. Sebaliknya, kebahagiaan yang seperti ini pada dasarnya adalah kesengsaraan.
6. Keberkahan, kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian
Kebahagiaan dalam arti keberkahan dapat dipahami dari QS. al-A’raf: 96; Huud: 48, 73; an-Nahl: 127; dan adz-Dzariyaat: 39. Kata barakah, sebagaimana yang terkandung dalam QS. al-A’raf: 96, oleh Quraish Shihab diartikan sebagai aneka kebajikan ruhani dan jasmani, sesuatu yang mantap, kebajikan yang melimpah beraneka ragam dan bersinambung.
Kolam dalam Bahasa Arab dinamai birkah, karena air yang ditampung dalam kolam itu menetap mantap di dalamnya dan tidak tercecer ke mana-mana. Ayat ini mengandung makna bahwa keberkahan Ilahi datang dari arah yang seringkali tidak diduga atau dirasakan secara material dan tidak pula dibatasi atau bahkan diukur. Teks ayat ini dan ayat-ayat lain yang berbicara keberkahan Ilahi di atas memberi kesan bahwa keberkahan tersebut merupakan curahan dari berbagai sumber, dari langit dan bumi melalui segala penjurunya. Dari sini bisa dipahami bahwa segala penambahan yang tidak terukur oleh indera disebut dengan berkah. Secara rinci makna barakah dapat dipahami pula dari makna yang terkandung dalam QS. al-An’am: 92.68
Adanya keberkahan pada sesuatu berarti terdapat kebaikan yang menyertai sesuatu tersebut. Misalnya, jika ada berkah dalam waktu yang diberikan Allah kepada seseorang, maka akan banyak kebaikan yang terlaksana dalam waktu itu, meskipun dalam waktu tersebut umumnya tidak banyak aktivitas yang dilakukan olehnya. Keberkahan makanan adalah cukupnya makanan yang sedikit untuk mengenyangkan orang banyak, meskipun pada umumnya makanan yang sedikit itu tidak dapat dimakan oleh orang yang banyak.
Dari kedua contoh ini, terlihat bahwa keberkahan berbeda sesuai dengan fungsi sesuatu yang diberkahi. Keberkahan pada makanan misalnya adalah dalam fungsinya mengenyangkan, menimbulkan kesehatan, menolak penyakit, mendorong aktivitas positif, dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi bukan dengan sendirinya secara otomatis, tetapi karena ada karena karunia Allah Swt. Karunia di sini bukan menafikkan adanya hukum sebab akibat yang telah ditetapkan Allah, tetapi maksudnya bahwa Allah menganugerahkan kepada siapa yang akan diberi keberkahan kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan huku-hukum tersebut seefisien dan semaksimal mungkin sehingga keberkahan tersebut hadir. Dalam hal keberkahan makanan misalnya, Allah Swt. menganugerahkan kemampuan kepada manusia yang akan diberi keberkahan makanan berupa aneka sebab yang ada sehingga kondisi badannya sesuai dengan makanan yang tersedia, misalnya kondisi makanan itu pun sesuai, sehingga tidak kadaluarsa, hilang, atau dicuri orang.
Intinya, keberkahan di sini bukan berarti campur tangan Allah dalam bentuk membatalkan sebab-sebab yang dibutuhkan untu lahirnya sesuatu.
Terkait dengan tema kebahagiaan, dengan memperhatikan beberapa penafsiran di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu indikator kebahagiaan seorang manusia adalah bahwa apabila ia mampu mengisi hidupnya dengan berbagai aktifitas kebaikan baik yang bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, maupun umat manusia secara umum. Aktivitas kebaikan di sini adalah segala sifat dan amal perbuatan yang dapat dinikmati manfaatnya oleh banyak orang, bermakna, dan membahagiakan dirinya. Itulah makna hidup yang berkah. Orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya berkah.
Kebahagiaan dalam arti salam (selamat, damai, atau sejahtera) dapat dipahami sebagai kebebasan dari segala macam kekurangan, apapun bentuknya, lahir maupun batin. Sehingga, seseorang yang hidup dalam salam akan terbebas dari penyakit, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Kata ini terulang di dalam al-Qur’an sebanyak 42 kali dengan beberapa maksud di bawah ini:
-
Sebagai ucapan salam yang bertujuan untuk mendo’akan sebagaimana tercantum dalam QS. adz-Dzariyat: 25 yang menceritakan kedatangan malaikat kepada Nabi Ibrahim As.
-
Keadaan atau sifat sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam QS. al- Maidah: 16 yang menggambarkan keadaan atau sifat jalan yang ditelusuri oleh orang-orang yang beriman.
-
Menggambarkan sikap mencari selamat dan damai, seperti firman Allah dalam QS. al-Furqan: 63 yang memuji hamba-hamba-Nya yang selalu berusaha untuk mencari kedamaian saat menghadapi orang-orang “jahil” di sekitarnya.
-
Sebagai sifat Allah Swt., sebagaimana tersurat dalam QS. al-Hasyr: 23.
Menurut Quraish Shihab, dalam konteks QS al-Qadr: 4, jika kata salam dipahami sebagai do’a, maka ayat ini menginformasikan bahwa para malaikat itu mendo’akan setiap orang yang menemuinya pada malam lailat al-qadr supaya terbebas dari segala kekurangan lahir batin. Jika kata salam dipahami sebagai keadaan, sifat, atau sikap, maka malam lailat al-qadr dipahami sebagai malam yang penuh kedamaian yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang menjumpainya, atau dapat pula dimaknai bahwa sikap para malaikat yang turun pada malam ini adalah sikap yang penuh damai terhadap mereka yang merasa berbahagia mencari dan mendapatkannya.
Dalam ayat yang lain yang berbicara tentang makna salam, terdapat beberapa ayat yang menggambarkan ucapan salam yang ditujukan kepada para penghuni sorga kelak, yaitu di antaranya QS. Yunus: 10 dan ar-Ra’d: 24, atau istilah dar as-salam (negeri yang penuh kedamaian) yang menggambarkan kondisi kehidupan sorga, yaitu antara lain dalam QS. al-An’am: 125-127 dan Yunus: 25.
Kata salam, jika disifatkan kepada sesuatu maka berubah menjadi salim. Kata ini sesungghnya memiliki akar yang sama dengan kata Islam, yang berasal dari kata kerja salima, yang sama-sama bermakna selamat. Dalam al-Qur’an, yaitu surat asy-Syu’ara: 89 dan surat al-Shaffat: 84, kata salim digandengkan dengan kata qalb (hati). Secara bahasa, qalb salim bermakna hati yang selamat dari penyakit atau kerusakan apapun. Adapun pengertian khususnya adalah hati yang tidak mengenal selain Islam. Untuk memiliki hati yang selamat, manusia harus menerapkan seluruh akhlak mu’min yang terkandung dalam al-Qur’an.
Pada hari akhir nanti tidak ada yang bermanfaat kecuali manusia yang datang denga membawa hati yang selamat. Artinya, hati orang yang kafir tidak mungkin sampai ke pantai kedamaian dan keselamatan di hari itu. Oleh karena itu, hati yang selamat harus bersih dari kekafiran, kesyirikan, keraguan, dan kebimbangan. Hati yang penuh kekakfiran, betapapun pemiliknya berbuat baik dan humanis, tetap tidak dapat menjadi hati yang selamat.
Jika dikatakan oleh seseotang yang kafir bahwa: “ Hatiku bersih karena aku sangat mencintai manusia dan selalu berusaha menolong mereka”, maka ini adalah pernyataan yang kosong, karena hatinya berisi kekafiran dan pengingkaran. Hatinya bukanlah hati yang selamat dan bersih, sebab ia mengingkari Pemilik dan Penguasa alam. Mencintai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan adalah sesuatu yang penting dan baik. Akan tetapi, nilai-nilai kemanusiaan tesebut harus terlebih dahulu dipahami secara benar, kemudian pemahaman ini harus berkesinambungan dan tidak terputus. Pemahaman semacam ini terkait dengan dengan iman. Tanpa iman, segala bentuk kebaikan, keindahan, dan kemuliaan hanyalah dusta, sementara, dan tidak bernilai.
Ringkas kata, hati yang selamat adalah tema yang sangat penting, karena al- Qur’an memposisikan hal ini sebagai ganti dari harta dan anak-anak, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. asy-Syu’ara: 88-89. Nasib seorang manusia di akhirat tergantung pada jawabannya atas pertanyaan berikut: Apakah ia hidup dalam keadaan diridhai ?, Apakah ia mati dalam keadaan diridhai ?, Mampukah ia dibangkitkan dalam keadaan yang diridhai ?, Mampukah ia menuju jalan Muhammad ?, Dapatkah ia sampai ke Telaga Kautsar? Apakah Rasulullah Saw. dapat melihatmu dari kejauhan dan mengenalimu? Rasulullah menegaskan bahwa pada Hari Kiamat beliau akan mengenali umatnya dan dapat membedakan mereka di antara seluruh umat. Ketika ditanya bagaimana hal itu terjadi, beliau menjawab, “Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalian mendatangiku dengan wajah yang bersinar terang karena bekas wudlu” (HR. Bukhori dan Muslim). Itulah salah salah satu manifestasi dan gambaran hati yang selamat.
Terlepas dari perbedaan makna ini, Ibnu Qayyim menyatakan pendapatnya seputar kedamaian dan ketenteraman hati. Ia berkata bahwa Hati yang damai dan tenteram akan mengantarkan pemiliknya dari ragu kepada yakin, dari kebodohan kepada ilmu, dari lalai kepada ingat, dari khianat menuju amanat, riya’ kepada ikhlas, lemah menjadi teguh, dan dari sombong menjadi tahu diri. 74 Inilah tanda jiwa yang telah mencapai derajat kedamaian, sebuah puncak kebahagiaan manusia.
7. Limpahan Karunia
Selain makna kebahagiaan di atas, makna kebahagiaan dapat dipahami pula dari kata “limpahan atau curahan karunia”. Kata ini terdapat dalam beerapa ayat al-Qur’an, misalnya QS. al-Baqarah: 199, 245, al-Maidah: 83, al- A’raf: 50, at-Taubah: 92, Yunus: 61, Ibrahim: 4, Shad: 26, al-Ahqaf: 8, dan al- Hadid: 11. Salah satu di antara yang dapat dibahas di sini adalah:
“ Dan penghuni neraka menyeru penghuni surge: “limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu”. Mereka (penghuni sura) menjawab: “sesuangguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir” (QS. al-A’raf: 50)
Ayat di atas mengisyaratkan bahwa al-faidh hanya diperuntukkan untuk para penghuni surga. Menurut Fethullah Gulen, istilah “limpahan karunia” dapat dimaknai dengan kebahagiaan atau kenikmatan. Al-Faidh dalam kehidupan duniawi adalah limpahan karunia Ilahi yang berkaitan dengan kehidupan hati dan spiritual manusia. Adapun di akhirat, اﻟﻔﯿﺾ adalah kedudukan dan kemuliaan yang diraih manusia, seperti masuk sorga, meraih ridha Allah, dan kehormatan melihat keindahan-Nya. Kandungan makna dari istilah ini begitu sangat luas dan mustahil bagi manusia untuk menjangkaunya secara tepat. Bisa saja terjadi bahwa berbagai limpahan karunia mendatangi manusia dari semua sisi, sedangkan ia sendiri tidak mengetahui dan merasakannya. Demikian pula, ketidakmampuan manusia mengetahui dan merasakannya termasuk karunia Allah Swt. atasnya., karena karunia terbaik-Nya adalah karunia yang tidak kita rasakan.
Dari sisi ini, lanjut Gulen, dapat dikatakan bahwa terdapat limpahan karunia Ilahi dan keberkatan pada semua ibadah yang dikerjakan manusia untuk Allah Swt. Betapa tidak terbayang sama sekali bahwa ada manusia yang menuju pintu-Nya lalu kembali dengan tangan kosong. Akan tetapi, manusia tidak boleh mengaitkan ibadahnya dengan limpahan karunia Ilahi atau kenikmatan yang didapatnya. Terkadang, shalat dilakukan saat seorang hamba sedang dalam kondisi spiritual yang sedang lemah, yaitu saat jiwa dan hatinya sempit. Secara lahiriah, shalat seperti ini dapat dikatakan payah, namun bisa saja shalatnya termasuk shalatnya yang paling baik atau paling diterima, karena ia melakukan shalat dalam kondisi lepas dari semua perasaan seraya tetap tidak lupa untuk menunjukkan penghambaannya kepada Allah Swt. Ia senantiasa tetap berdiri di pintu-Nya dan tidak pernah meninggalkannya, karena ia yakin bahwa Allah akan mengabulkan segala doanya. Dengan kata lain, kondisi di mana seorang hamba tidak menerima limpahan karunia Ilahi tidak membuat keikhlasannya lenyap. Inilah sebuah penghambaan yang tulus dan murni.
Dari sisi yang berbeda, Gulen menulis bahwa pencapaian kedudukan spiritual tidak boleh menjadi tujuan ibadah seorang hamba. Junaid al-Baghdadi berkomentar tentang orang-orang yang mengerjakan kewajiban ibadah demi mendapatkan surga. Menurutnya, ibadah yang seperti ini adalah ibadah para hamba surga, padahal surga tidak layak menjadi tujuan ibadah. Ibadah dikerjakan, karena Allah memerintahkannya, atau dalam rangka meraih ridha-Nya. Artinya, sebab hakiki ibadah adaah perintah Allah. Jadi, manusia mengerjakan berbagai kewajiban ibadah karena Allah memerintahkannya kepada mereka. Jika ada di antara mereka melakukan shalat kepada Allah, karena takut kepada neraka, maka orang itu adalah hamba neraka. Bagimana mungkin ia dapat menjdi hamba Allah Swt.? Manusia harus tetap melaksanakan shalat meskipun dalam kondisi iman (spiritual) yang sedang menurun, yaitu ketika tidak mendapatkan limpahan karunia Ilahi. Tangisan dan rintihan manusia, di samping menjadi sarana untuk mendapatkan limpahan karunia Allah dan keberkahan, juga dapat menjadi sarana ujian dan cobaan. Alhasil, manusia tidak dapat menetapkan penilaiannya secara pasti di hadapan Allah.
Sumber : Dr. Muskinul Fuad, M. Ag, Psikologi kebahagiaan dalam al-qur’an : Tafsir Tematik atas Ayat-ayat al-Qur’an tentang Kebahagiaan, IAIN Purwokerto